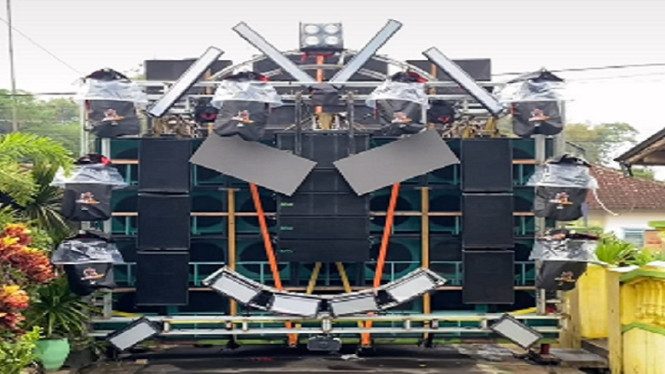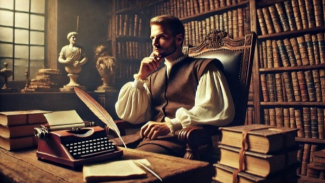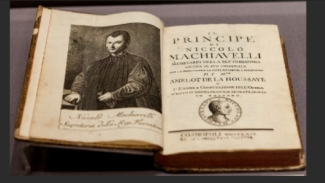Kenapa Anak Ketika Dilarang Semakin Melakukannya? Ini Penjelasan Psikologi Anak
- Pixabay
Lifestyle –Banyak orang tua mengeluhkan hal serupa anak tidak patuh meskipun sudah berkali-kali dilarang. Bahkan, semakin tegas larangan diberikan, semakin sering pula anak melanggarnya. Misalnya, dilarang bermain gadget sebelum tidur, justru anak sembunyi-sembunyi melakukannya. Atau dilarang keluar rumah sore hari, justru sengaja menghilang dari rumah pada jam tersebut.
Fenomena ini bukan sekadar nakal, melainkan berkaitan erat dengan cara kerja psikologis anak. Salah satu penjelasan kuat datang dari, psikolog anak dari Harvard Medical School dan penulis buku The Explosive Child, yang dikenal karena pendekatannya pada perilaku menantang anak, Dr. Ross W. Greene.
Menurut Greene, saat anak merasa dikendalikan secara berlebihan tanpa diberi ruang untuk berdiskusi, maka yang muncul adalah reaktansi psikologis, yaitu dorongan alamiah untuk mempertahankan otonomi atau kebebasan pribadi.
“Ketika kita terlalu fokus pada kendali, anak justru merasa kehilangan kontrol atas dirinya. Dan anak-anak yang merasa kehilangan kontrol akan berusaha merebutnya kembali dengan cara menolak, melawan, atau membangkang,” jelas Greene dalam salah satu wawancaranya di Psychology Today.
Anak bukan tidak mengerti bahwa suatu hal dilarang, tapi mereka terdorong untuk melakukannya karena ingin membuktikan bahwa mereka punya kuasa atas dirinya sendiri. Semacam reaksi “balas dendam” terhadap rasa terkekang.
Teori Reaktansi: Saat Kebebasan Dibatasi, Hasrat Melanggar Meningkat
Fenomena ini juga dijelaskan secara ilmiah oleh Reactance Theory (Teori Reaktansi) dari psikolog Jack Brehm. Menurut teori ini, ketika seseorang merasa kebebasannya direnggut, maka muncul reaksi emosional berupa penolakan, dan keinginan untuk melakukan hal yang dilarang jadi makin besar.
Dalam konteks anak-anak, larangan keras bisa terasa seperti perampasan hak. Contoh sederhananya:
- Larangan: “Jangan makan permen itu sekarang!”
- Respons alami: Anak akan makin penasaran, lalu mencoba makan diam-diam.
Bukan karena anak tidak tahu permen itu tidak baik sebelum makan malam, tapi karena ia merasa dikekang dan ingin membuktikan bahwa dia tetap bisa mengambil keputusan sendiri.
Pola Asuh Otoriter Memperparah
Greene juga menyoroti bahwa pola asuh yang sangat otoriter yakni penuh perintah tanpa diskusi mendorong anak menjadi lebih reaktif.
Dalam pola ini, anak tidak diberi ruang untuk bertanya mengapa. Akibatnya, mereka hanya melihat larangan sebagai bentuk kekuasaan sepihak, bukan bentuk kasih sayang atau perlindungan.
“Jika kita hanya berfokus pada kepatuhan, kita kehilangan peluang untuk membangun keterampilan pemecahan masalah dan kemampuan regulasi emosi anak,” kata Greene.
Ia menyarankan agar orang tua beralih ke pola komunikasi kolaboratif, di mana anak diberi ruang untuk memahami alasan di balik aturan dan diajak menyelesaikan masalah bersama.
Contoh Nyata: Larangan vs Kolaborasi
Misalnya, saat anak sering bermain HP di malam hari:
- Cara lama (otoriter): “Pokoknya mulai sekarang, HP disita jam 7 malam. Titik!”
- Respons anak: Merasa dikekang, lalu menyembunyikan HP dan bermain diam-diam.
Bandingkan dengan pendekatan kolaboratif:
- Cara kolaboratif: “Kak, aku lihat kamu sering susah bangun pagi. Mungkin karena HP? Kita cari solusi bareng yuk, gimana baiknya soal waktu main HP?”
- Respons anak: Merasa dilibatkan, lebih mungkin mengikuti kesepakatan karena ia berkontribusi dalam keputusan itu.
Gaya Komunikasi yang Menenangkan, Bukan Mengancam
Greene juga menekankan pentingnya tone komunikasi. Anak-anak sangat sensitif terhadap nada bicara dan cara penyampaian.
Larangan yang disampaikan dengan nada tinggi, membentak, atau ancaman, akan langsung memicu reaksi defensif. Namun, larangan yang disampaikan dengan tenang, empatik, dan berbasis diskusi, justru bisa diterima lebih baik.
Misalnya:
- Daripada berkata, “Jangan lari-lari di toko! Kamu bikin malu aja!”,
- Cobalah: “Ayo jalannya pelan ya, supaya kita nggak nabrak orang lain.”
Mendidik Anak Memahami Alasan di Balik Aturan
Anak-anak perlu tahu alasan mengapa sesuatu dilarang. Saat mereka paham tujuannya, mereka lebih mungkin menaatinya. Ini bagian dari pendidikan logika dan empati sejak dini.
Jika dilarang nonton TV lama-lama karena bisa merusak mata atau mengganggu waktu tidur, jelaskan konsekuensinya dengan bahasa yang sesuai usia anak. Beri pilihan atau negosiasi yang tetap memberi anak rasa punya kontrol.
Saat Larangan Tetap Dibutuhkan, Tapi Harus Bijak
Tentu ada situasi di mana larangan tetap harus diberlakukan dengan tegas, misalnya demi keselamatan seperti, angan menyentuh kompor, kangan menyeberang jalan sendirian atau jngan membuka pintu untuk orang asing.
Namun, larangan semacam ini tetap bisa disampaikan secara empatik dan edukatif, bukan sekadar otoritatif. Gunakan kalimat seperti:
“Aku nggak izinkan kamu sentuh itu karena panas dan bisa melukai tanganmu. Nanti Mama ajari caranya kalau sudah waktunya, ya.”
Fenomena “semakin dilarang, semakin dilakukan” bukan tanda anak nakal, tapi respons psikologis alami terhadap kehilangan kontrol. Dr. Ross Greene mengajak orang tua untuk mengganti pendekatan dari kendali penuh ke kolaborasi yang penuh empati.
Dengan komunikasi yang terbuka, penyampaian yang bijak, dan melibatkan anak dalam solusi, aturan rumah akan lebih mudah diterima. Bukan karena anak takut, tapi karena anak paham dan merasa dihargai.